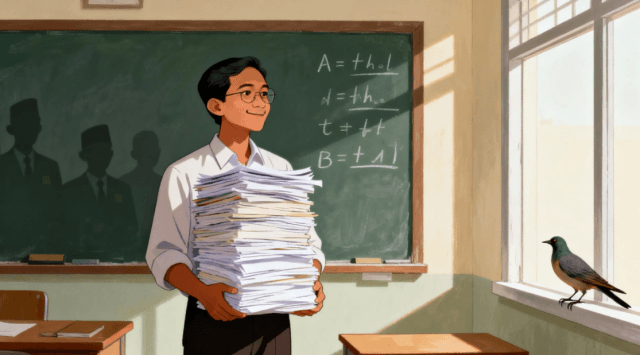
Dulu, sewaktu SD, kami sekelas pernah ditanya soal cita-cita oleh guru. Pertanyaannya sederhana, seperti pertanyaan yang muncul tiap tahun ajaran baru:
“Kelak mau jadi apa?”
Saya, dengan kejujuran seorang bocah yang belum mengenal hirarki kemuliaan profesi, menjawab,
“Saya ingin menjadi tukang becak.”
Di mata saya waktu itu, tukang becak adalah pekerjaan yang sangat logis: gowes → capek → dibayar. Sesederhana hukum sebab-akibat. Namun Bu guru langsung memandang saya seperti saya baru saja mengajukan permohonan menjadi administrator web judol.
“Jangan begitu… cita-cita itu harus mulia,” katanya.
Lalu beberapa teman menyahut ingin menjadi guru. Dan Bu guru tersenyum, mengangguk, lalu memberikan pujian yang hanya bisa diberikan seorang guru kepada profesinya sendiri. Cita-cita menjadi guru dianggap lebih mulia—entah berdasarkan takaran apa.
Aneh memang. Hari itu, kelas kami seperti ruang lelang kemuliaan: siapa menyebut profesi yang pas di hati Bu guru, dialah pemenangnya.
Bertahun-tahun kemudian, sebagian dari mereka benar-benar menjadi guru. Seakan-akan pujian masa kecil itu berubah menjadi wahyu profesi. Dan dibanding saya mereka lebih beruntung, sebab saya masih gini-gini saja, jadi tukang becakpun tidak terkabul.
Tetapi zaman punya selera humor sendiri. Guru yang dulu diagungkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kini justru harus mengumpulkan tanda jasa berupa sertifikasi, SK, portofolio, PPG, laporan kinerja, dan pelatihan-pelatihan yang lebih menguras tenaga daripada mengajar murid yang tidak bisa membedakan “di” sebagai kata depan dan “di-” sebagai imbuhan.
Segalanya demi satu kata yang akhir-akhir ini sering terasa seperti jargon brosur seminar:
Profesionalitas.
Padahal, kalau mau jujur, profesional itu—secara definitif—adalah seseorang yang menjalankan pekerjaannya dengan keahlian, integritas, tanggung jawab moral, dan standar mutu yang jelas, bukan seseorang yang sekadar lolos verifikasi dokumen. Profesional adalah soal kapasitas, bukan sekadar kelengkapan folder.
Dan di sinilah sarcastic tragedy itu terjadi: formalitas dianggap sebagai profesionalitas, sementara kapasitas sering kali diletakkan di kursi belakang sambil menunggu giliran untuk digunakan.
Paulo Freire, orang pintar dalam hal pendidikan– kalau tidak salah– pernah berkata,
“Education does not change the world. Education changes people. People change the world.”
Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia. Lalu manusialah yang mengubah dunia.
Ironisnya, sistem kita kadang justru menjadikan guru sebagai manusia yang tidak boleh banyak berubah. Guru harus ikut kurikulum A, lalu B, lalu A revisi C yang isinya masih mirip B tapi beda judul (anda bingung? Sama, saya juga sangat bingung). Guru harus patuh pada petunjuk teknis yang ditulis dengan gaya bahasa formal yang bahkan pembuatnya kadang lupa maknanya.
Guru akhirnya menjadi semacam pion yang harus manut ke sana–manut ke sini. Kapasitasnya ada, idealismenya ada, tetapi ruang geraknya sering kali seperti meja kelas yang sudah patah satu kaki: bisa digunakan, tapi harus rela miring sedikit.
Saya kemudian bertanya dalam hati:
Andai waktu kecil saya dibiarkan bercita-cita menjadi tukang becak, mungkinkah saya tumbuh dengan pemahaman bahwa kemuliaan tidak melekat pada nama profesinya, melainkan pada cara seseorang menjalankan profesi itu?
Tukang becak bisa mulia kalau bekerja jujur. Guru bisa tidak mulia kalau mengajar hanya untuk absen dan angka kredit. Tidak ada yang otomatis suci atau hina, kecuali perilakunya.
Tetapi lagi-lagi, frekuensi humor Tuhan kadang tinggi. Profesi yang dulu disebut “pahlawan” kini justru harus berlari-lari mengejar standar, sertifikat, dan akreditasi agar dianggap layak. Padahal anak-anak yang mereka ajar lebih membutuhkan keteladanan, bukan sekadar pengajar yang ahli mengunggah laporan bulanan.
Pada akhirnya, Hari Guru—dan profesi guru secara keseluruhan—selalu mengingatkan saya pada satu hal:
Bahwa negara boleh saja membuat aturan berlapis-lapis; birokrasi boleh saja membangun pagar formalitas setinggi-tingginya; tetapi seorang guru sejati tetap lahir dari kapasitas, empati, dan kemampuan melihat murid sebagai manusia.
Sertifikat bisa dibuat, gelar bisa dicetak, laporan bisa difotokopi, tetapi kapasitas dan kemanusiaan tidak bisa direkayasa.
Dan untuk itulah, guru tetap lebih besar daripada sistem yang sering memperlakukannya seperti pion.
Selamat Hari Guru.
Semoga para guru kembali dimanusiakan, bukan sekadar disertifikasi.
Dan semoga profesionalitas tidak lagi disempitkan menjadi formalitas.


