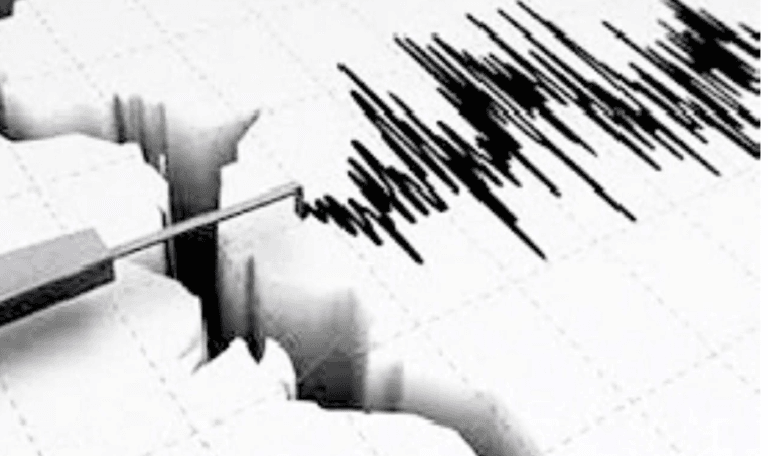Negara sering bicara tentang efisiensi, efektivitas, dan penyesuaian kebijakan. Di ruang rapat mungkin terdengar masuk akal. Namun di rumah-rumah kecil, yang terdengar justru kompor yang makin boros, pupuk yang makin tipis, dan motor yang mendadak gampang ngambek.
Kita tidak sedang menolak kebijakan—kita hanya bertanya pelan: mengapa yang paling dulu terasa selalu dari arah dapur dan dompet rakyat jelata?
Subsidi untuk rakyat jelata selalu menjadi kambing hitam yang empuk. Setiap kali anggaran negara terasa membebani APBN, subsidi langsung dituding sebagai biang kerok yang harus diringankan, dialihkan, atau kalau perlu: pelan-pelan dihapus. Dulu, di masa pemerintahan SBY, konversi minyak tanah ke LPG menjadi contoh paling sopan bagaimana negara memindahkan beban anggarannya. Alasannya terdengar masuk akal: subsidi minyak tanah terlalu besar, tidak tepat sasaran, dan membengkak setiap tahun.
Padahal, minyak tanah bukan barang mewah. Ia adalah sandaran dapur orang-orang kecil yang tidak punya kayu bakar, sekaligus bahan bakar ublik—penerang malam bagi rumah-rumah yang masih gelap sebelum listrik masuk. Ironisnya, minyak tanah sendiri adalah produk olahan fraksi minyak bumi yang justru lebih murah diproduksi dibanding LPG. Jadi persoalannya bukan pada minyak tanahnya—melainkan pada sistem distribusi yang bocor ke mana-mana, mafia yang meraup untung, dan ketidakmampuan negara menutup lubang-lubang itu. Konversi pun dilakukan, tabung gas dibagikan, dan perlahan minyak tanah ditarik dari peredaran. Selesai sudah: subsidi geser, anggaran “lega”, dan kita diminta memahami bahwa ini demi efisiensi.
Cara ini, setidaknya, masih dapat dianggap “sopan”. Ada proses transisi, ada penjelasan, ada narasi perbaikan. Negara tidak serta-merta mencabut begitu saja, melainkan mengganti barangnya. Walau tetap ada kepentingan ekonomi besar di baliknya, kita masih bisa menahan diri untuk tidak terlalu sinis.
Padahal sejak dulu negara sebenarnya sudah sangat berpengalaman untuk tahu bahwa kebocoran subsidi yang merugikan anggaran bukan terjadi di tangan rakyat kecil, melainkan di lingkar kekuasaan dan distribusinya sendiri. Mestinya, dari pengalaman panjang itu, negara sudah hafal di mana lubangnya dan siapa yang bermain. Yang harus diberantas ya itu—bukan malah rakyat kecil yang disuruh menanggung akibatnya.
Namun belakangan, pola pengurangan subsidi tampaknya berkembang ke bentuk yang lebih kreatif. Misalnya dalam urusan pupuk subsidi. Setiap musim tanam, petani seperti berjudi dengan nasib: kadang pupuk tersedia, kadang seperti hilang begitu saja. Kelangkaan pupuk terjadi di hampir semua daerah, dan alasan yang disampaikan selalu itu-itu saja—kuota terbatas, data tidak sinkron, pendistribusian di lapangan kacau. Tetapi anehnya, pupuk nonsubsidi—yang harganya berkali lipat—tidak pernah benar-benar langka. Ia selalu tersedia, rapi berjajar di etalase, menunggu petani yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam agar tanamannya tidak mati sia-sia.
Inilah cara yang lebih “tidak sopan”: membuat barang subsidi sulit diakses, entah karena distribusi dipersulit, stok dibatasi, atau sengaja dibiarkan dikelola oknum yang bekerja seperti makelar. Lama-lama masyarakat akan pindah sendiri ke barang non-subsidi karena kebutuhan tidak bisa menunggu birokrasi. Negara tinggal angkat tangan: “Kami menyediakan, tapi kelangkaan di lapangan bukan salah kami.” Praktis, subsidi berkurang tanpa harus mencabutnya secara resmi.
Dan sekarang, kita menghadapi bentuk ketiga: cara yang paling tidak sopan, paling halus sekaligus paling menyakitkan—menurunkan kualitas barang subsidi itu sendiri. Contoh paling dekat dengan hidup sehari-hari: Pertalite.
Pertalite hari ini bukanlah Pertalite lima tahun lalu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pemilik motor dan mobil mengeluhkan mesin yang mbrebet, cepat kotor, cepat panas, bahkan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Mekanik-mekanik kecil di bengkel pinggir jalan juga mengangguk pelan: iya, banyak motor masuk karena gejalanya sama. Bukan karena salah perawatan, tetapi karena bahan bakarnya seperti tidak beres.
Ya, meskipun secara resmi pemerintah tidak pernah mengakui adanya tambahan zat tertentu yang membuat kualitas Pertalite menurun, kecurigaan itu tumbuh karena pengalaman orang-orang sendiri: motor tiba-tiba mbrebet, tersendat, dan lebih cepat “ngambek” dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketika gejala muncul serempak di banyak tempat, wajar jika masyarakat mulai bertanya-tanya—ada apa sebenarnya dengan bahan bakar yang katanya masih sama ini?
Pada titik ini, masyarakat dipaksa memilih: tetap menggunakan Pertalite yang kualitasnya buruk dan berisiko merusak mesin, atau pindah ke Pertamax yang lebih stabil namun harganya tentu tidak disubsidi. Dan seperti strategi sebelumnya, pemerintah tidak perlu mengumumkan apa-apa. Tidak perlu konferensi pers panjang. Tidak perlu menanggung amarah publik. Masyarakat akan berpindah dengan sendirinya, karena tidak ingin motornya mogok di tengah jalan.
Jean Baudrillard pernah menulis bahwa dalam masyarakat modern, tanda-tanda sering bekerja lebih kuat daripada kenyataan itu sendiri. Pertalite hari ini mungkin secara resmi masih “produk yang sama”, tetapi tanda-tanda kerusakannya sudah menggantikan kenyataan yang dulu kita kenal. Yang tersisa hanyalah simulasi bahan bakar bernama Pertalite—ia ada pada nama, tetapi berbeda pada kenyataan.
Mungkin inilah negara yang “hemat anggaran tapi boros kenyataan”. Subsidi tidak diumumkan hilang, tetapi dibuat tidak layak, tidak tersedia, atau tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, masyarakat dipaksa membayar lebih mahal, sementara negara dapat berkata: kami tidak mencabut apa pun.
Dan sebagaimana kata Ivan Illich, “Institusi modern kerap mengklaim melayani publik, tetapi secara diam-diam merampas kemampuan masyarakat untuk mengatur hidupnya sendiri.” Mungkin itu pula yang terjadi dengan subsidi: dari semula alat untuk melindungi rakyat kecil, perlahan berubah menjadi permainan angka yang bisa diakali, dipindahkan, bahkan dibiarkan membusuk kualitasnya.
Pertanyaannya bukan lagi apakah subsidi dihapus, tetapi dengan cara apa subsidi itu dipreteli pelan-pelan. Kita mungkin tidak menyadarinya dalam sekejap, tetapi perubahan kecil yang terus menumpuk akan mengarahkan kita ke kesimpulan yang sama: bahwa negara tidak lagi menghilangkan subsidi melalui kebijakan eksplisit, melainkan lewat strategi yang lebih sunyi.
Belajar dari contoh-contoh kasus subsidi ini, ada satu hal yang selalu berulang: apa pun bentuk kebijakan negara—entah diberi nama konversi, efisiensi, atau penyesuaian—yang pertama kali dan paling perih merasakan dampaknya selalu rakyat jelata yang miskin. Mereka yang dapurnya bergantung pada api kecil, bukan pada argumentasi di meja rapat; mereka yang hidupnya rapuh, tetapi justru menjadi bantalan terbesar setiap kali negara ingin menambal anggarannya.
Sunyi, tapi nyerinya merembes sampai ke kantong dan mesin motor kita.
Jadi, sedisiplin apa pun kita membayar pajak, kalau masih masuk kategori rakyat jelata dan miskin, negara tetap punya cara menggencet sampai gepeng. Pajaknya masuk, hidupnya tetap seret. Begitulah hukumnya yang tak pernah diumumkan.