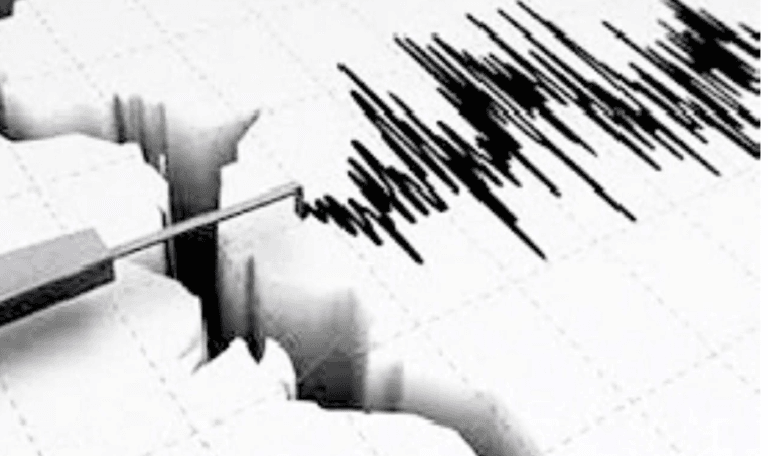Sebagian dari kita mestinya masih segar ingatannya soal “wahabi lingkungan” yang dicetuskan oleh Gus Ulil. Ya, soal mereka yang dianggap konservatif menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana ekologis, dan bencana alam tentunya. Tentu, tulisan ini tidak lantas ingin menyelisihi Gus Ulil, saya tidak berani, saya takut kuwalat, khawatir ilmu saya tidak barokah; dan tulisan ini juga tidak ingin mengurangi ta’dzim saya kepada orang-orang yang ‘alim seperti Gus Ulil. Pula, tulisan ini tidak sedang menjadikan bencana sebagai objek satir atau candaan. Tapi begini… tulisan ini memang berangkat dari bencana yang terus datang bertubi-tubi belakangan ini.
Ngeten, Gus. Rasanya apa yang disebut sebagai “wahabi lingkungan” itu seperti sedang mengeluarkan tulah, atau tuahnya, ya? Karena bencana seolah makin getol datang tanpa menunggu hari baik, juga tidak peduli ringkel. Kadang saya bertanya-tanya: jangan-jangan kita memang sedang dikembalikan ke fitrah paling dasar bahwa alam itu sebenarnya sakti mandraguna; ia sabar, iya. Tapi juga punya batas sabar–yang kalau sudah lewat–bisa membuat Danyangan pun ikut ngungsi karena dampak bencana alam.
Kita lihat data BNPB sepanjang setahun terakhir. Hampir tiap minggu ada saja kabar longsor, banjir bandang, kekeringan ekstrem, hingga cuaca yang tidak karuan. Itu belum termasuk laporan satelit yang menunjukkan bagaimana hutan kita terkoyak seperti kain bekas yang dijahit ulang berkali-kali. Dan ironinya, publik seperti sudah terlalu akrab dengan pemberitahuan darurat: “Awas banjir,” “Awas cuaca ekstrem,” “Awas potensi tanah bergerak, ” dan “Awas-awas yang lain.” Lama-lama, awasnya itu justru yang menakutkan, karena berarti kita seolah sudah menormalisasi bencana sebagai rutinitas musiman.
Padahal, kita semua tahu bencana tidak pernah benar-benar “alami” ketika manusianya sendiri rajin merusak alam. Alam ini seperti ibu yang telaten merawat anak yang bandel. Sekali dua kali dimaklumi. Tiga kali masih dimaafkan. Tapi kalau anaknya tetap tidak tahu diri, ya ibu itu pun bisa marah. Dan ketika alam marah, kita tidak hanya menanggung air bah, tetapi juga rasa malu, karena kita sebenarnya tahu siapa yang menyebabkan semua ini.
Beberapa bencana terakhir bahkan seperti mengingatkan kita dengan cara paling pahit. Longsor yang terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya habis ditebangi. Banjir bandang yang menghantam pemukiman yang dibangun dengan penuh percaya diri di atas jalur air tua. Cuaca ekstrem yang berdampak pada gagal panen, membuat harga beras naik, dan di republik ini, naiknya harga beras lebih menakutkan daripada kuliah umumnya para ahli.
Dan kita semua tahu: yang menjadi korban tidak mungkin anggota DPR, menteri, jajaran elit organisasi keagamaan, atau presiden. Yang menjadi korban tetaplah rakyat jelata. Mereka yang rumahnya terbuat dari papan, yang dapurnya terkadang mengepul, terkadang tidak tapi tetap harus hidup, dan yang setiap kali bencana datang selalu menjadi headline media dengan judul klise: “Warga Mengungsi, Butuh Bantuan.”
Rakyat jelata yang tidak pernah hadir di meja rapat penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya. Mereka yang tidak pernah ikut tanda tangan proyek-proyek besar, tetapi harus mengungsi karena tebing di belakang rumah mereka jebol setelah perusahaan-perusahaan besar menebangi bukit tanpa keraguan sedikit pun.
Dan kita mungkin sepakat, bahwa semua itu berawal bukan sekadar dari “butuh,” tetapi dari sesuatu yang lebih gelap: keserakahan. Kebutuhan bisa dimusyawarahkan, tetapi keserakahan adalah watak yang terus menganga. Ia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan tidak pernah bersedia berhenti meskipun alam sudah memberi tanda-tanda keras. Karena kalau hanya “butuh,” manusia tentu masih punya rem. Tapi kalau sudah “serakah,” jangankan rem, spion saja tidak dipakai. Yang penting gas pol-rem dol, hasil cepat, untung besar.
Keserakahan inilah yang membuat sebagian orang merasa bumi ini seperti properti pribadi. Hutan dianggap halaman belakang yang bebas ditebang. Sungai dianggap saluran air yang bebas ditimbuni. Gunung dianggap peluang investasi yang bebas ditambang. Dan ketika akibat dari semua itu datang dalam bentuk bencana, mereka tinggal mengangkat bahu sambil berkata: “Ini cobaan.”
Padahal, sebagian cobaan itu diproduksi oleh tangan mereka sendiri. Tapi memang manusia punya bakat luar biasa untuk tidak merasa bersalah ketika masih ada pihak lain untuk disalahkan: termasuk cuaca, takdir, dan hal-hal abstrak yang tidak bisa protes.
Di sisi lain, rakyat jelata terus menjadi korban yang paling patuh. Mereka jarang mengeluh, jarang menuntut, jarang berteriak. Mereka hanya mencoba bertahan. Ironinya, mereka yang paling hati-hati terhadap alam justru yang paling dulu terkena dampaknya. Sedangkan mereka yang menentukan kebijakan sering kali duduk nyaman sambil menikmati laporan PowerPoint yang rapi, tanpa bau lumpur, tanpa suara tangis pengungsi, tanpa rasa getir kehilangan rumah.
Maka di tengah situasi ini, “wahabi lingkungan” yang dahulu sempat menjadi istilah satir, kini justru tampak seperti gambaran kelompok paling waras. Mereka yang dianggap konservatif menjaga alam ternyata justru sedang menunjukkan apa yang sejak dulu kita abaikan: bahwa yang disebut “modernitas” sering kali tidak lebih dari keberanian membuang sampah ke masa depan.
Dan masa depan itu sudah tiba sekarang dalam bentuk bencana demi bencana.
Mungkin memang saatnya kita berhenti melihat alam sebagai sesuatu yang bisa terus-menerus dimanipulasi. Alam tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita, atau berapa jumlah jamaah kita, atau berapa banyak proyek yang kita kerjakan. Alam tidak bisa disuap, tidak bisa dilobi, dan tidak punya sekjen.
Pada akhirnya, ketika bencana datang, ia datang menyapu tanpa peduli riwayat politik, ideologi, atau status sosial. Bedanya, mereka yang punya uang bisa pindah, sementara rakyat jelata hanya bisa pasrah. Dan mungkin di situ letak ironi terbesar negeri ini: alam marah kepada semua, tetapi yang menanggung paling berat adalah mereka yang paling sedikit salahnya dan, tentu saja, yang tidak banyak uang.
Bencana yang kita lihat hari ini bukan hanya peringatan, tetapi juga cermin. Dan cermin itu menampilkan wajah kita apa adanya: bangsa yang terlalu berani merusak, terlalu takut berubah, dan terlalu lihai menyalahkan langit untuk dosa-dosa yang kita lakukan sendiri di bumi.
Dan percayalah… alam tidak cukup hanya bisa dijaga dengan doa, qunut nazilah dan tahlilan. Ia menuntut tindakan-tindakan yang nyata, bukan ritual yang dijadikan selimut ketakberdayaan. Karena alam, pada akhirnya, tidak tunduk pada retorika. Ia hanya tunduk pada perlakuan kita.