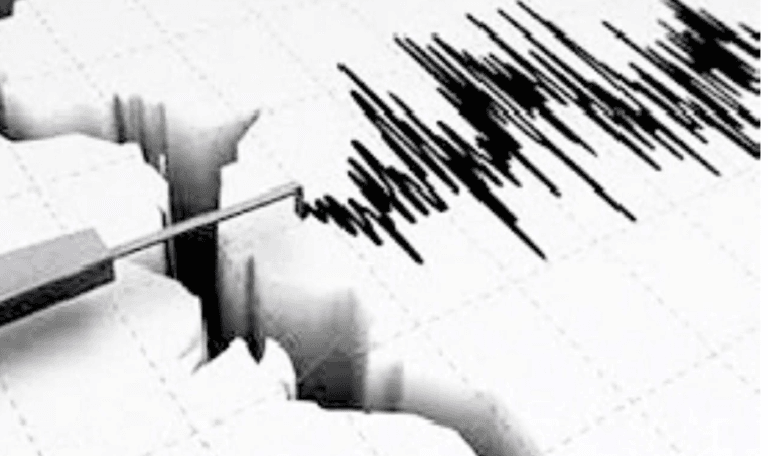Isu kesehatan mental generasi muda belakangan ini semakin sering diperbincangkan. Istilah seperti burnout, kecemasan, depresi, hingga kehilangan makna hidup kerap muncul dalam percakapan sehari-hari maupun di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), dan lainnya. Fenomena ini menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan.
Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi—yang berlandaskan sains dan rasionalitas—seharusnya mampu membantu manusia menata kehidupan secara lebih terukur, efisien, dan pasti.
Namun ironisnya, generasi muda justru menghadapi krisis psikologis yang semakin kompleks. Pertanyaannya kemudian, mengapa kepastian ilmiah tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan batin manusia?
Sejak lama, ilmu pengetahuan diposisikan sebagai sumber kebenaran yang objektif dan universal. Melalui pendekatan ilmiah, manusia diyakini mampu memahami realitas secara rasional dan bebas dari prasangka.
Pandangan ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Kehadiran sains telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, teknologi, hingga tata kelola sosial.
Namun persoalan muncul ketika kebenaran ilmiah tidak lagi dipahami sebagai alat pembebasan, melainkan berubah menjadi standar tunggal dalam menilai kesuksesan dan keberhasilan hidup. Dalam kehidupan modern, sains dan rasionalitas sering hadir dalam bentuk angka, target, dan capaian. Prestasi akademik diukur melalui indeks nilai, produktivitas dinilai dari output, dan kesuksesan dipersempit pada parameter yang dapat diukur secara kuantitatif.
Tanpa disadari, sudut pandang semacam ini menciptakan tekanan psikologis yang besar, khususnya bagi generasi muda. Mereka yang gagal memenuhi standar tersebut kerap merasa tidak cukup rasional, tidak produktif, bahkan muncul perasaan tidak pantas untuk hidup. Di sinilah krisis mental mulai menemukan akarnya.
Dalam konteks ini, pembahasan mengenai filsafat ilmu menjadi sangat relevan. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran yang berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari konteks sosial, nilai, serta kepentingan manusia. Kebenaran ilmiah bersifat tentatif, terbuka untuk dikritik, dan tidak selalu mampu menjawab seluruh kompleksitas pengalaman manusia—terutama yang bersifat eksistensial dan emosional.
Ketika ilmu pengetahuan diperlakukan seolah-olah netral dan absolut, manusia justru berisiko merasa terasing dari dirinya sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam isu kesehatan mental generasi muda yang tidak bisa dilepaskan dari relasi yang timpang antara manusia dan pengetahuan.
Di satu sisi, generasi muda dituntut untuk selalu rasional, logis, dan produktif. Di sisi lain, emosi, kegagalan, dan kerapuhan jiwa sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal, pengalaman psikologis manusia tidak selalu dapat dijelaskan—apalagi diselesaikan—melalui rumus dan data statistik. Ada ruang di mana sisi kemanusiaan membutuhkan empati, refleksi, dan pemaknaan, bukan sekadar tolak ukur berupa angka.
Kondisi ini semakin diperparah oleh peran media sosial. Algoritma media sosial secara tidak langsung membentuk standar kehidupan tertentu yang berdampak pada kondisi emosional penggunanya. Generasi muda terus-menerus dihadapkan pada perbandingan hidup yang tidak realistis. Standar kesuksesan ditampilkan seolah-olah objektif dan ilmiah, seakan semua manusia harus berada pada titik pencapaian yang sama.
Padahal, standar tersebut dibentuk oleh konstruksi sosial dan ekonomi tertentu. Ketika realitas personal tidak sesuai dengan standar yang ditampilkan, yang muncul sering kali bukan kritik terhadap sistem, melainkan rasa bersalah dan kegagalan pada diri sendiri.
Dalam situasi seperti ini, filsafat ilmu menawarkan sikap kritis terhadap cara kita memaknai kebenaran. Filsafat ilmu membantu membedakan antara kebenaran metodologis dan kebenaran yang bermakna bagi kehidupan manusia. Tidak semua hal yang benar secara ilmiah otomatis baik secara etis. Kesadaran ini penting agar ilmu pengetahuan tidak berubah menjadi ideologi baru yang menekan, alih-alih membebaskan.
Refleksi semacam ini juga menjadi sangat mendesak dalam dunia pendidikan. Selama ini, pendidikan sering menekankan aspek kognitif dan capaian akademik, sementara kesehatan mental peserta didik kerap terabaikan. Seharusnya, ilmu pengetahuan tidak hanya diajarkan sebagai kumpulan fakta dan teori, tetapi juga sebagai proses pencarian makna yang manusiawi.
Dengan pendekatan tersebut, generasi muda tidak hanya tumbuh menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara emosional dan matang secara reflektif.
Merefleksikan kembali klaim kebenaran ilmiah bukan berarti menolak sains. Justru sebaliknya, hal ini merupakan upaya untuk mengembalikan ilmu pengetahuan pada tujuan dasarnya: meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemahaman, penjelasan, prediksi, dan pengendalian. Di tengah krisis psikologis generasi muda, kita perlu kembali bertanya: apakah ilmu pengetahuan masih memberi ruang bagi keraguan, kegagalan, dan jiwa yang rapuh sebagai bagian sah dari pengalaman manusia?***
Penulis: Rahmanda Sukma Ayu merupakan mahasiswa semester tiga Program Studi PPKn di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memiliki minat pada dunia kepenulisan. Aktif menulis opini, cerpen, dan artikel sebagai bentuk refleksi atas realitas sosial.