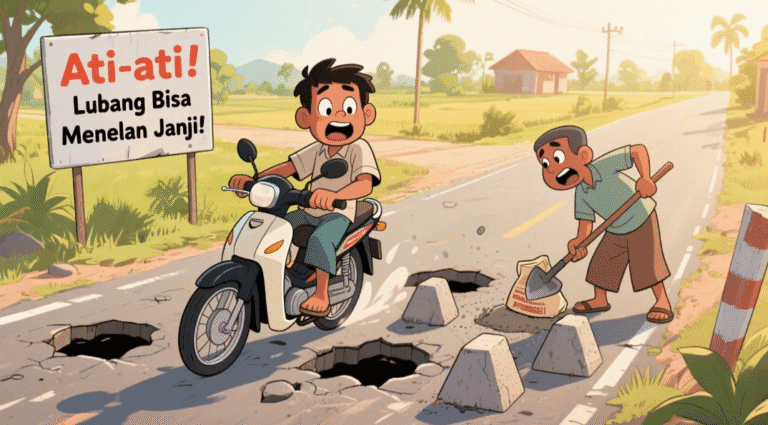Di era media sosial, kebenaran seolah tak lagi ditentukan oleh proses berpikir yang panjang dan dapat dipertanggungjawabkan. Cukup dengan video singkat, narasi meyakinkan, dan jumlah penonton yang besar, sebuah opini personal dapat berubah menjadi rujukan bersama. Media sosial, terutama platform seperti TikTok menjadi ruang di mana setiap orang bukan hanya bebas berbicara, tetapi juga merasa paling benar.
Fenomena ini tampak dari maraknya konten yang membahas isu kesehatan, pendidikan, hingga sains berdasarkan pengalaman pribadi. Tanpa data dan tanpa proses verifikasi, pandangan tersebut kerap diterima begitu saja oleh publik. Pengalaman individual dijadikan standar umum, padahal dalam ilmu pengetahuan, pengalaman tunggal tidak cukup untuk menghasilkan kebenaran yang dapat digeneralisasi. Di sinilah krisis otoritas ilmu bermula.
Dalam filsafat ilmu, pengetahuan ilmiah dibedakan secara tegas dari opini sehari-hari. Ilmu pengetahuan lahir melalui proses yang sistematis seperti observasi, pengujian, kritik, dan keterbukaan terhadap koreksi. Kebenaran ilmiah tidak bergantung pada siapa yang menyampaikan, melainkan pada bagaimana pengetahuan tersebut dibangun dan diuji. Otoritas ilmu, dengan demikian, bukan persoalan popularitas, tetapi soal tanggung jawab epistemologis.
Masalahnya, media sosial tidak bekerja dengan logika tersebut. Algoritma platform digital dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna. Konten yang sering ditonton, disukai, dan dibagikan akan terus diperkuat, menciptakan ruang gema (echo chamber). Dalam ruang ini, pengguna lebih sering bertemu pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri.
Sebuah opini kemudian terasa semakin benar bukan karena telah diuji, melainkan karena terus dikonfirmasi secara berulang.
Berbagai studi tentang disinformasi digital menunjukkan bahwa konten yang bersifat emosional dan sederhana lebih mudah menyebar dibandingkan penjelasan ilmiah yang kompleks. Survei global mengenai kepercayaan publik juga mencatat adanya penurunan kepercayaan terhadap pakar dan institusi ilmiah di tengah derasnya arus informasi digital. Kondisi ini menjelaskan mengapa ilmu pengetahuan sering kali kalah bersaing dengan opini personal yang dikemas secara menarik.
Fenomena tersebut terlihat jelas di TikTok. Banyak konten yang membahas sains atau kesehatan hanya berdasarkan pengalaman pribadi, lalu diklaim seolah berlaku umum. Tanpa konteks, tanpa batasan, dan tanpa rujukan ilmiah, konten semacam ini tetap dipercaya karena terasa dekat dan meyakinkan. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, validitas tidak ditentukan oleh kedekatan emosional, melainkan oleh proses verifikasi yang ketat.
Krisis otoritas ilmu ini bukan berarti ilmu kehilangan kebenarannya, melainkan cara kita memaknai kebenaran yang bergeser. Ilmu disamakan dengan opini, sementara viralitas dianggap sebagai legitimasi. Ketika semua suara diperlakukan setara tanpa mempertimbangkan dasar pengetahuannya, pengetahuan ilmiah kehilangan posisi istimewanya sebagai hasil berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan?
Pertama, membangun kesadaran epistemologis di ruang digital. Tidak semua informasi memiliki bobot yang sama. Membiasakan diri bertanya “berdasarkan apa?” dan “bagaimana prosesnya?” menjadi langkah awal untuk membedakan opini dari pengetahuan ilmiah.
Kedua, literasi digital perlu dimaknai lebih luas dari sekadar kemampuan menggunakan media sosial. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang cara kerja algoritma, kesadaran akan bias informasi, serta kehati-hatian dalam menjadikan pengalaman personal sebagai rujukan kebenaran.
Ketiga, ilmu pengetahuan perlu hadir di ruang publik dengan bahasa yang lebih manusiawi. Ilmu tidak harus disampaikan dengan arogansi atau jargon yang sulit dipahami.
Komunikasi ilmiah yang terbuka dan kontekstual justru dapat membantu menjembatani jarak antara dunia akademik dan masyarakat.
Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah lahir secara instan. Ia dibangun melalui proses berpikir yang panjang, terbuka terhadap kritik, dan berlandaskan tanggung jawab moral. Media sosial bukanlah musuh ilmu pengetahuan, tetapi tanpa kesadaran kritis, ia dapat menjadi ruang yang mereduksi makna kebenaran.
Di tengah banjir informasi hari ini, tantangan kita bukan sekadar berbicara, tetapi belajar menahan diri untuk berpikir. Kebenaran seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa sering ia muncul di layar, melainkan oleh seberapa kuat ia diuji. Di sinilah pentingnya mengembalikan otoritas ilmu, bukan sebagai kebenaran yang absolut, melainkan sebagai proses pencarian yang jujur dan bertanggung jawab.
Penulis: Azzahra Putri Pramesti adalah mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ia tertarik pada kajian filsafat ilmu, literasi digital, media sosial, serta dinamika pengetahuan dan demokrasi di ruang publik.